Cerita
dari beragam jaman, saling jalin menjalin dalam tiap pilar, rangka, atau bahkan
terperangkap dalam warna dinding yag makin memudar. Ia hidup dalam masa tanpa
massa, bersanding dengan kemegahan waktu. Menjemput tiap jiwa yang luruh dalam
elaborasi fakta. Jiwa yang terpaut dan luluh pada masa lalu, hidup ribuan
tahun. Ia menjadi bagian dari bangunan berdinding lapuk, yang ditawarkan
pemerintah menjadi destinasi dalam tur. Hati yang terpaut dalam kejayaan masa
lalu, jadi bagian sejarang yang tak lekang dimakan waktu.
“Ngomong
apa, sih?”
Langkah
Rumi menuju masjid Kauman terhenti. Ia menoleh, memandang kearah gadis bertubuh
mungil yang ikut menghentikan langkahnya. Rambut hitam sebahunya beterbangan
tertiup angin sore hari.
“What? I said nothing,” Ia membela diri.
Rumi
memicingkan mata, meragukan kebenaran pengakuan si gadis. Ia mendekatkan
tubuhnya pada si gadis, lalu menyentuh lengannya, lambutnya, dan terakhir,
hidungnya.
“Kamu
ngapain?” gadis itu mulai risih. Ia mundur selangkah, membuat dress putih yang
dikenakannya melambai-lambai.
“Elo
beneran bukan hantu?”
Gadis
itu menggeleng.
“Terus
lo siapa?”
“Kan
tadi pagi aku udah cerita,” jawabnya sambil berlalu menuju tempat wudhu wanita.
Darimana
datangnya suara itu? Rumi yakin seklai Ia mendengar suara gadis asing yang
tiba-tiba pagi tadi hadir di kamar homestay
yang ditinggalinya. Dema, begitu Ia menyebutkan diri, menggumamkan sesuatu
tentang bangunan dan sejarah.
Ugh!
Lupakan. Barangkali Ia Dema cuma fantasi yang datang karena gue terlalu stress.
Rumi berusaha menenangkan diri. Tapi sia-sia saja karena setelah Ia menunaikan
sholat maghrib, sosok Dema nampak tak jauh darinya. Melambaikan tangan dengan
memasang wajah ceria. Rumi memutar jalan, mencari jalan lain. bermaksud menghindari
Dema, Ia melewati jalan disamping selasar maghrib, memelankan langkahnya agar
Dema tidak mengikutinya.
“Are you trying
to escape?”
Rumi
terlonjak kaget. Tiba-tiba saja Dema sudah berada disampingnya dan berbisik.
Melihat wajah Rumi yang memucat, Dema tertawa terbahak-bahak.
“Rumi,
aku bukan hantu,” Dema kembali menjelaskan sambil berjinjit. Tangannya
terangkat untuk membenahi kerah kemeja yang dikenakan Rumi. “kalau aku hantu,
buat apa aku sholat?”
“Orang-orang
nggak bisa lihat kamu,”
Dema
mengerutkan alis. Lalu Ia memandang sekeliling dan menemukan soerang anak kecil
bertubuh tambun yang berdiri tak jauh darinya. Dema menghampirinya, lalu
menggelitiki pipi si bocah sambil tertawa kecil. Kemudian, sang Ibu menghapiri
keduanya sambil mengobrol singakt dengan Dema. Rumi tercengang. Ia kehabisan
kata-kata.
“Elo
siapa, sih?”
“I should be your wife,” Dema tersenyum,
lalu buru-buru menambahkan, “Should be
someday.”
“What?”
Dema
mengedikkan bahu. “Nggak tahu, deh. Tante Dina yang bicara kaya gitu,”
“Terus,
lo mau apa?”
“Makan!”
Dema menjawab dengan ceria. Lalu Ia menarik tangan Rumi kearah gerobak makanan
yang berjajar di pelataran masjid.
*
Barangkali
gue harus ke psikiater.
Rumi
tercengang melihat Dema yang ‘lolos’ dari pandangan teman-teman di ruang tamu homestay. Tubuhnya yang mengenakan loose dress berwarna putih tampak ringan
melewati teman-temannya yang sedang berkerumun, ada yang membaca buku, sedang
yang lain menonton televisi. Dema menunduk, melirik buku tua yang ramai-ramai
dibaca kawan Rumi. Ia kembali melangkah, lalu duduk sejenak disamping Gehitto,
ikut menonton televisi. Lalu Dema berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar.
“Woi!
Ngapain lo disitu?”
Teriakan
Gehitto menyadarkan Rumi yang masih memandang kearah Dema. Ia gelagapan, masih
terheran-heran dengan cara Dema kembali menjadi tak kasat mata.
“Tadi
ada cewek duduk di sebelah lo. Badannya kecil, pakai dress warna putih.
Rambutnya sebahu, pipinya merah,”
“Lo
ngigau, ya?” sahut Aru keheranan. “ini kan homestay
cowok. Mana ada cewek yang berani main kesini?”
Rumi
makin keheranan. Ia melewati teman-temannya lalu masuk ke dalam kamar. Sedang
berdiri di pinggir tempat tidur, Dema melipat celana jins yang pagi tadi Rumi
biarkan tergeletak di lantai, bekas Ia gunakan kemarin malam. Belum habis rasa
herannya, Dema sudah mengangsurkan handuk yang dilipat rapi. Diatasnya,
terdapat sikat bersama pasta gigi, kaus dan celana untuk tidur, dan minyak kayu
putih.
“Jangan
langsung tidur, bersih-bersih dulu,”
Mengacuhkan
alis Rumi yang mengerut keheranan, Dema kembali ke pigngir tempat tidur,
melipat semua baju yang berserakan dimanapun. Rumi tinggal sekamar dengan Aru
dan Gehitto. Tapi anehnya, Dema mampu memisahkan mana baju milik Rumi, Aru, dan
Gehitto.
“Kamu
ini kebiasaan, deh,” Dema nyeletuk. “Kalau berantakan gini, kamu sendiri lho
yang susah,”
Tepat
ketika Dema menutup pintu lemari, Aru dan Gehitto masuk ke dalam kamar. Mata
Rumi masih lekat pada Dema yang duduk di pinggir tempat tidur, memandanginya.
“Lo
sehat?” Aru menepuk pipi Rumi. “Kok lo pucat gini, sih?”
Gehitto
ikut memandang kearah pandang Rumi. Mencari sesuatu yang membuat sahabatnya
berdiri mematung dan pucat. Yang ditemuinya hanya kamar yang bersih dan cukup
wangi. Ia mengernyit. Wangi vanilla khas cewek.
“Lo
abis tidur sama cewek, ya?”
Dema membelalakkan mata dan melompat kaget,
membuat Rumi langsung tersadar.
“Apaan,
sih?” Rumi membela diri.
“Kok
gue ngerasa ada wangi cewek disini?” Gehitto keheranan.
“Itu
aku, Rumi,” ujar Dema sambil tertawa kecil.
“Tuh,
kan! Lo denger nggak dia ngomong apa?”
Aru
dan Gehitto memandang satu sama lain. Keheranan.
“Ini,
ada cewek diantara kita. Lagi duduk di kasur gue. Dia yang beresin kamar kita,”
Rumi bersikeras, lalu menyentuh bahu Dema. “Lo ngomong sesuatu, dong!”
“Nggak
bisa, Rumi. Aku lagi nggak pengen dilihat orang,” Dema melepaskan cengkeraman
tangan Rumi.
“Kenapa?”
“Emangnya
kamu mau digosipin bawa cewek masuk ke dalam kamar?” Dema tersenyum kecil, lalu
berbalik dan menghempaskan tubuhnya keatas kasur. “Gehitto sama Aru tidur di
ranjang atas kan? Aku mau tidur disini, ya? kamu disini aja,” ujarnya sambil
menepuk sisi yang masih kosong disampingnya.
“Rumi,
lo ngomong sama siapa?” Gehitto bertanya, lagi-lagi mengikuti arah pandang
Rumi.
Rumi
kehabisan kata-kata. Ia mengambil handuk dan peralatan mandi yang disiapkan
Dema, lalu masuk ke dalam kamar mandi.
*
“Gue
mulai nggak waras,”
Homestay yang disewa
kelompok kerja Rumi memang pas sekali untuk mereka. Memiliki lima kamar, rumah
bergaya lama itu cukup diisi seluruh anggota kelompok. Sebagai ketua dan
konseptor, ketiganya memilih kamar di lantai teratas. Tentu saja untuk
mendapatkan privilege berupa balkon
yang sedang mereka tempati sekarang. Dema sudah tertidur pulas di ranjang
bagian bawah. Tadi, Rumi sempat menutupi tubuh Dema dengan selimut karena
tubuhnya terasa sangat dingin. Sambil menikmati kopi hitam, ketiganya duduk di
pinggir balkon, menatap langit Jogja yang sedang rekah dengan banyaknya
bintang.
“Si
cewek itu?”
“Namanya
Dema,” sahutnya.
“Kok
lo bisa ketemu dia?” Gehitto bertanya.
*
Jam
berapa ini?
Ugh!
Ini hari Minggu. Day to sleep. Setelah
berhari-hari penuh gue menggadaikan kehidupan gue demi social project dan ditemani bergelas-gelas kopi, rasanya gue pantas
mendapatkan tidur yang layak. Barangkali sejam, dua jam tambahan sampai sore.
Lalu gue mandi, makan dan, hmph! Ngapain lagi? it’s a free day! Kenapa gue harus bangun karena telepon bangsat
ini? Siapa yang ganggu, sih? Masih juga jam 10 pagi. Oh, Fariz. Wait, ngapain si brengsek nelpon gue?
“Lo
tau nggak, gue mau tidur,” gue menahbiskan kata tersebut sebagia pengganti halo
sejak sebulan lalu Ia terus meracau karena kehilangan calon istrinya.
“Gue
cuma mau bilang kalau gue lagi di Surabaya. Mau makan enak, nggak?”
“Untungnya
gue lagi di Surabaya, dan gue nggak perlu ketemu lo,” gue menyahut.
“Hah?
Lo lagi dimana?”
“Jogja,”
“Ngapain?
Liburan?”
“Bukan
urusan lo,”
“Rumi,
nggak boleh bilang gitu!”
Wait! Shit! Kenapa gue
denger suara cewek?
“Suara
siapa, tuh?” Fariz bertanya dengan nada penasaran.
“Bukan
siapa-siapa,”
Terdengar
teriakan girang di seberang sana yang bisa langsung gue simpulkan kalau itu
adalah teriakannya.
“Finally! Adek gue ngerti juga gimana
caranya bersenang-senang!” Ujarnya penuh semangat. “So how’s night? Lo nggak lupa pakai kondom, kan?”
“Brengsek!”
gue menyumpah serapah. “Nanti gue telpon lagi,”
“Have fun, lil
bro!”
Darimana
asalnya suara itu? Gue menyibakkan selimut dan memandang sekeliling. Sedetik kemudian
menyadari gue ada di ranjang atas, tempat Gehitto tidur. Pagi-pagi sekali,
mereka berdua dan anggota lain pergi ke Mangunan untuk melepas penat. Jelas
saja kamar kami sepi. Lalu darimana suara itu?
Tunggu,
lagipula sejak kapan Ibu pengurus membiarkan cewek masuk kemari? Berarti, suara
tadi Cuma ada di kepalaku. Tapi, dariamana Fariz bisa tahu? Masa ada hubungan
persaudaraan kasat mata, ya? Ah, bullshit!
Gue mau tidur lagi.
“Sudah
siang, Rumi. Ayo bangun,”
Gue
terlonjak kaget. Suara itu nyata! Datangnya dari arah balkon.
“Hari
ini ada tur sejarah yang pengen kamu datangi. Yakin mau tidur lagi?”
Berusaha
menyingkirkan rasa takut, gue mengintip dari atas ranjang, mencari asal suara
yang benar datang dari balkon. Berasal dari seorang gadis bertubuh mungil yang
bersandar di pagar balkon. Ia mengenakan dress berwarna putih, selaras dengan
warna kulitnya. Rambutnya panjang sebahu. Pipinya merona merah, apalagi ketika
Ia tersenyum padaku.
“Selamat
pagi,” Ia menyapa. “Bangun, yuk. Aku sudah siapkan baju, tas dan sarapanmu,”
Gue
pasti Cuma mimpi. Mengacuhkan kehadirannya, gue kembali menarik selimut dan
kembali terlelap. Entah berapa lama kemudian, gue kembali terjaga dengan dia
yang duduk bersila disamping gue. Membaca buku, sambil menikmati teh hijau
beraroma madu. Sementara tangan kanannya memegang buku, tangan kirinya
mengusap-usap kepalaku.
“Kapan
terakhir keramas? Berminyak banget, deh,”
Spontan
gue melompat bangun, mengucek mata dan memandang kearahnya. Iseng, gue melirik
kearah jam dinding, sekedar mengecek apa jarum jam masih menunjuk ke angka 10
dan gue Cuma bermimpi. Ternyata, sekarang sudah jam 12 siang. Voila! Gue nggak
sedang bermimpi. Dan gadis ini? Gue menyentuh lengannya untuk memastikan apa
dia tembus pandang atau enggak.
“Rumi,”
ujarnya lembut ketika gue menyentuh lengannya. “Gue bukan setan, hantu, roh,
atau apapun itu yang ada di kepalamu,”
“Lalu
lo siapa?”
“Dema,”
“Just
Dema?”
Ia
mengangguk, tanpa sedikitpun mengangkat wajahnya dari buku yang sedang
dibacanya.
“Lalu
Dema, apa yang bikin lo datang kemari?”
“Tante
Dina,”
Gue
memandangnya tak percaya.
“Mama?”
Ia
mengangguk.
“Tapi,
Mama udah pergi tahun lalu,” mau nggak mau, gue mengembalikan ingatan kelam
setahun lalu. “kecelakaan, mobil, darah, meninggal,”
Melihat
perubahan nada suara gue, Ia menutup bukunya dan menyentuh tangan gue lalu
mengusapnya.
“That’s why I’m here,” Ia berujar. “Tante
Dina minta tolong aku buat mengembalikan Amygdala di kepalamu,”
“Darimana
kamu kenal Mama?”
“Aku
lagi ada di persimpangan. Antara menunggu urusan dunia yang belum selesai, dan
tuntutan untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan Tante Dina ada disana
bersamaku. Tante Dina selalu cerita kalau kamulah satu-satunya alasan kenapa
beliau nggak segera melanjutkan perjalanan. Tante Dina tahu amygdala yang kamu
punya nggak lagi berfungsi setelah Ia pergi,”
“Amygdala?”
Ia
menghela napas panjang. Sedkit kesal karena kau tidak tahu dengna istilah yang
dibicarakannya.
“Bagian
terkecil dari otak yang mengatur emosi dan perasaan. Secara nggak langsung,
amygdala punyamu nggak berfungsi karena kamu merasa sedih luar biasa,”
“Jadi,
kamu udah meninggal? Seperti Mama?”
“Nope.
Belum,” Ia mengedikkan bahu. “bahkan aku nggak tahu sebenarnya aku ini apa,”
Gue
kembali menyentuh lengannya, memastikan dia bukan hantu.
“But,
yang aku tahu adalah aku harus mengembalikan amygdala di kepalamu karena aku
punya amygdala yang super duper kuat,”
Gue
mencibir.
“Mahluk
nggak jelas,”
*
“And
then, this girl ruining my whole day!” Rumi melanjutkan cerita sambil sesekali
melirik kearah Dema yang terlelap. “Karena gue merasa nggak enak sekamar sama
cewek, akhirnya gue keluar...”
“Finally!
Ada juga orang yang bisa bikin elo keluar dari kamar di hari Minggu,” Aru
menjentikkan jari dengan senang. “tapi sayangnya orang itu malah mahluk halus,”
“Lalu
lo kemana?” Gehitto tetap fokus.
“Ke
antah berantah,” sahut Rumi dengan kesal
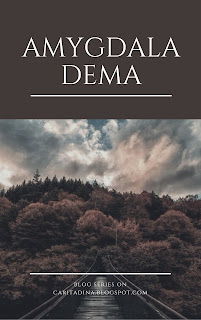
Komentar
Posting Komentar